Setelah duduk di kelas akhir, biasanya orang-orang akan mulai mempersiapkan dirinya untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi, namun yang dilakukan Jihan tidaklah demikian. Gadis itu malah sibuk menghabiskan waktunya ke sana- ke mari. Bermain-main tanpa rasa iri saat menyaksikan seluruh teman-temannya sibuk mempersiapkan diri untuk sebuah masa depan yang lebih baik.
Jihan tidak peduli mengenai itu. Setelah melihat perpisahan kedua orangtuanya, Jihan tidak lagi peduli pada sebuah rancangan masa depan.
Apa Jihan tidak mempunyai mimpi seperti sahabat-sahabatnya yang lain? Seperti Arisha yang selalu mempertahankan nilainya, bersungguh-sungguh setiap kali membicarakan perihal kedokteran, memiliki tokoh inspirator acuan masa depan dan berusaha mencari universitas terbaik untuk dijadikan perantara mewujudkan mimpi. Atau seperti Keisha yang sejak dini sudah melatih kemampuannya dalam mendesain pakaian, mempelajari mengenai ilmu membangun bisnis sejak dini dan mulai mempersiapkan brand butik atas namanya sendiri, bermimpi suatu saat nanti brandnya dapat masuk ke jajaran brand ternama Negara Indonesia bahkan sampai Mancanegara.
Apakah Jihan tidak memiliki mimpi apapun?
Tentu saja Jihan memiliki mimpi, namun Jihan memaksa mengubur dan melupakan mimpinya dalam-dalam saat ia tidak lagi mempercayai sebuah masa depan tanpa dukungan keluarga yang optimal. Jihan berpikir bahwa setelah keluarganya terbelah dua, tidak ada keinginannya yang tersisa.
“Pulang sekolah pergi main yuk? Gue males pulang ke rumah,” ajak Jihan, sembari merangkul kedua pundak sahabatnya.
Arisha dan Keisha bertukar pandang lalu melayangkan tatapannya pada Jihan secara bersamaan.
“Gue harus pulang, ada les buat persiapan tes masuk Universitas nanti. Maaf Han, lo kan tau sendiri gue bener-bener mau hasil yang maksimal kali ini,” tolak Arisha tak enak. Jihan tertawa kecil seraya menganggukkan kepala lalu kini beralih menatap Keisha yang juga tampak bingung.
“Gue juga gak bisa, Han. Hari ini gue mau ketemu salah satu desainer inspirator gue dari dulu. Susah ngatur jadwal beliau, ini juga berkat Papa gue bisa ketemu dia. Maaf ya, Han,” sesal Keisha, menatap Jihan tak tega.
Jihan tertawa sumbang, menyembunyikan rasa iri yang membelenggu hatinya.
“Santai aja, gue bisa kok pergi sendiri.” Jihan mengatakan itu sembari menepuk kedua sahabatnya, lalu pergi mendahului mereka.
Arisha dan Keisha menatap punggung Jihan yang semakin menjauh. Punggung itu seolah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, namun meski Jihan sudah berusaha keras untuk terlihat sebaik itu, Arisha dan Keisha sudah tahu bahwa keadaan Jihan tidak sebaik kelihatannya. Sejak kedua orangtua Jihan berpisah, banyak sekali yang berubah dari gadis itu. Gadis yang penuh semangat dan gigih dalam meraih apapun yang dia inginkan, tiba-tiba tidak lagi peduli soal keinginan. Katanya, segala keinginan hanyalah sebuah beban. Untuk itu, Jihan mulai mengabaikan semua keinginannya termasuk mimpi yang dulu sangat ia elu-elukan.
Jihan sempat menjadi orang yang paling peduli dengan mimpi.
Jihan sempat menjadi orang yang paling peduli dengan mimpi.
“Gue harus jadi penulis terkenal! Lo tau Asma Nadia yang udah keliling ke berbagai Negara karena menulis, kan? Nah suatu saat nanti, gue akan mengikuti jejaknya,” ucap Jihan menggebu. Arisha dan Keisha hanya menganggukkan kepala seraya mencibir bahwa ucapan Jihan tidak akan sesederhana kedengarannya. Namun saat itu, meski Arisha dan Keisha tidak mempercayai mimpi Jihan, JIhan tetap bersikeras bahwa suatu saat nanti dia akan mampu mewujudkannya.
Saat Jihan melihat kedua orangtuanya bertengkar hebat, saling melempar kalimat cacian dan memutuskan berpisah tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada anak-anaknya kelak, sebagai anak pertama yang masih berusia empat belas tahun saat itu, Jihan sangat membenci kedua orangtuanya. Apalagi saat mereka dengan seenak jidat menentukan siapa yang tinggal dengan siapa. Mulai memisahkan Jihan dengan adik-adiknya.
Sejak saat itu, Jihan tidak lagi memikirkan mimpinya. Jangankan untuk meneruskan kerajinanya menulis setiap hari, banyak membaca saja ia sudah enggan. Jihan lebih tertarik memperhatikan mimpi adik-adiknya dan melupakan mimpinya sendiri, menguburnya dalam-dalam dan melupakan bahwa ia pernah bermimpi setinggi itu.
“Ma, Jihan pulang.” Jihan membuka pintu rumah, yang seketika disambut oleh Nura, adik kecilnya yang baru saja masuk sekolah dasar.
“Kakak!” sorak gadis kecil itu, seraya memeluk kaki Jihan. Jihan mengusap kepala Nura lembut lalu mengecupnya. Setelah itu Nura kembali berlari ke ruang televisi.
Jihan melanjutkan langkahnnya, namun belum sempat masuk ke kamar, ibunya memanggil dari arah dapur. Membuat Jihan mau tak mau harus memutar langkahnya dengan malas.
“Ada apa, Ma?” tanya Jihan di ambang pintu.
Sarah membelakangi Jihan, ia sibuk membersihkan sayuran di wastafel.
“Ada amplop cokelat di meja, kata Papamu itu dokumenmu masuk ke Universitas. Papamu sudah mengurus semuanya, jadi kamu tinggal masuk kuliah. Gak perlu ikut tes,” ujar Sarah sembari menunjuk amplop yang dimaksud menggunakan dagunya.
Jihan menatap amplop itu tidak minat seraya menganggukkan kepala, “Iya, Jihan ikut aja,” katanya sembari berbalik, tak ada niatan untuk melihat dan mengambil dokumennya.
“Eh, kamu gak mau liat? Itu cocok atau nggak jurusan yang papamu pilih, kalau gak cocok kan masih bisa diubah.” Sarah membersihkan kedua tangannya lantas membuka amplop itu. Jihan tidak menanggapi, ia hanya memperhatikan setiap ekspresi ibunya.
“Papamu pilih akuntansi, mungkin dia mau kamu menjadi seorang akuntan, Jihan. Gimana? Kamu udah punya jurusan yang sebelumnya sudah dipikirkan?” tanya Sarah, sembari menatap putri sulungnya.
Jihan menghembuskan napas seraya menggeleng, “Tidak ada. Jihan tidak pernah memikirkannya.”
Sarah terdiam, menelan salivanya susah payah saat menyadari bahwa kini putrinya tidak lagi seceria dan seambisius dulu.
“Jihan ikut keputusan Papa aja,” lanjutnya seraya melanjutkan niat untuk masuk ke kamar. Merebahkan tubuhnya yang lelah dan mengistirahatkan pikirannya yang terus saja mengatakan dirinya bodoh karena tidak mau berterus terang. Jihan menghembuskan napas berat lantas mengambil handuk untuk membersihkan diri, melupakan mimpinya yang sempat terlintas lagi.
***
Beberapa bulan kemudian, semuanya berubah. Teman-teman Jihan sebagian besar berhasil dengan usahanya, sebagian lagi kecewa dan menggunakan alternatif lain yang sebelumnya sudah disiapkan. Arisha berhasil memasuki Universitas yang diinginkannya. Begitupun dengan Keisha yang sejak awal memang tidak pernah khawatir mengenai Universitas. Keisha memiliki kedua orangtua yang mendukung dia secara penuh baik dari segi finansial ataupun kasih sayang. Keisha tidak pernah kekurangan apapun.
Jihan pun mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, dengan pelajaran-pelajaran yang sama sekali tidak Jihan minati. Namun hari-harinya tetap ia jalani seperti biasa. Meski tanpa gairah, Jihan tetap menjalaninya dengan serius, Jihan tidak pernah ingin memberi hasil yang buruk kepada kedua orangtuanya. Meski harus mengorbankan kesenangan dan keinginannya, Jihan selalu mencoba melakukan yang terbaik.
“Jihan, bagaimana kuliahmu? Nyaman?” Sarah bertanya saat Jihan baru saja meletakkan tas dan membuka sepatunya.
Jihan menganggukkan kepalanya, “Lumayan, Ma,” jawab Jihan sembari membuka lemari es, mengambil sebotol air mineral dingin.
“Mama mau kamu hidup senang, Han. Cobalah sesekali lakukan apa yang kamu inginkan, jangan terus-terusan mengikuti kemauan Papa atau Mama.”
Jihan bergeming saat mendengar Sarah berkata demikian. Bukan tak ingin, rasanya Jihan tak pantas memiliki keinginan setelah melihat penderitaan ibunya selama ini. Jika dengan menjadi anak yang penurut bisa membuat Papanya bersikap baik, maka Jihan akan melakukannya.
“Iya, Ma,” Jihan menyahut pendek seraya meninggalkan Sarah untuk memasuki kamarnya. Percakapan mereka selalu saja berakhir seperti itu beberapa tahun terakhir.
Di dalam kampus banyak sekali kumpulan komunitas menulis. Memikirkan perkataan ibunya, Jihan sempat mengumpulkan keberanian untuk mengikuti kata hati. Sesekali melakukan kegiatan yang memang hatinya inginkan, namun meski semester telah berlalu, keberanian Jihan tak kunjung terkumpul. Hingga suatu hari, Sarah memasuki kamar Jihan, menghampiri gadis itu yang sibuk mengerjakan tugas-tugas kuliah.
Meski ragu, Sarah tetap menghampiri dan duduk di bibir ranjang putrinya. Sembari membawa sebuah buku berwarna biru langit yang Sarah temukan saat mereka pindah rumah. Sarah menyodorkan buku itu ke hadapan Jihan, membuat mata Jihan terbelalak saat melihatnya. Jihan mengira bahwa buku ini tertinggal di rumahnya yang lama dan tidak pernah ditemukan siapapun, ia tak pernah mengira bahwa ibunya lah yang menemukannya.
“Maaf, Mama baca semua isinya.”
Jihan menghela napas seraya mengusap sambul buku tersebut. Buku yang tak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun namun seolah masih terawat dengan baik.
“Mama baca dan tahu semua mimpimu. Kenapa sekarang tidak dilanjutkan? Belum terlambat untuk mewujudkannya. Mama yakin kamu pasti bisa menjadi penulis seperti yang kamu inginkan,” ucap Sarah sembari mengusap lembut pundak putrinya.
Jihan tersenyum seraya menggelengkan kepala, “Jihan sudah lama melupakan mimpi ini, Ma. Tidak usah dipikirkan.”
Sarah menatap putrinya nanar, Jihan tak pandai membohongi ibunya. Sarah melihat jelas bahwa di sudut mata putrinya, mimpi itu masih ada. Hanya saja Jihan sedang berusaha keras membohongi dirinya sendiri.
“Jihan mau membuat Mama senang tidak? Setelah Papa pergi, kebahagiaan Mama hanya bergantung pada anak-anak Mama. Jika kamu seperti ini, kamu pikir Mama senang? Kamu pikir Mama tidak merasa terbebani? Kamu pikir, Mama tidak merasa bersalah? Tolong mengerti perasaan Mama, perasaan seorang ibu. Mama sedih melihat kamu jadi seperti ini. Setiap malam Mama selalu menyesalinya, mau sampai kapan kamu membuat Mama terus tertekan seperti ini? Mama sudah mencoba kuat, Jihan. Tolong jangan seperti ini.” Sarah mengungkapkan segalanya sembari menangis keras, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan.
Jihan tercenung, pikirannya seolah baru saja kembali dari mimpi yang panjang. Benar apa yang dikatakan ibunya, bukankah bersikap egois seperti ini hanya akan berakhir menyakiti perasaan ibunya?
Jihan beranjak dan memeluk ibunya, mengusap punggung wanita paruh baya yang sangat Jihan sayangi.
“Maafin Jihan, Ma. Jihan tidak sadar bahwa selama ini Mama sudah terlalu banyak menanggung luka,” bisik gadis itu, sembari memeluk ibunya lebih erat lagi.
***
Setelah malam itu, perlahan Jihan mulai menjadi dirinya sendiri. Jihan tidak lagi mengabaikan keinginannya, Jihan tidak lagi melupakan mimpinya. Jihan mulai mengikuti beberapa komunitas menulis entah di kampus atau di flatfom online. Jihan mulai aktif mempelajari ilmu-ilmu kepenulisan yang sempat ia abaikan. Perubahannya itu, berhasil membuat Arisha dan Keisha tersenyum bahagia melihatnya. Jihan kembali optimis dan bergairah melanjutkan mimpi.
Langkah signifikan pertama yang Jihan lakukan adalah saat mengikuti kompetisi menulis di kampus dan di kompetisi pertamanya, Jihan sudah berhasil memasuki finalis tiga besar dengan hadiah yang lumayan menggiurkan.
Jihan menunjukkan bakatnya, Jihan kembali berusaha keras melanjutkan mimpinya yang sempat tertunda.
Arisha dan Keisha memeluk Jihan bangga lantas menertawakan Jihan yang mereka anggap sudah bersikap pengecut beberapa tahun terakhir.
“Gue belom terlambatkan buat jadi Asma Nadia masa depan?” tukasnya seraya tertawa.
Ada banyak cara dalam menyikapi permasalahan yang datang. Saat merasa begitu patah, akan ada dua kemungkinan yang terjadi pada seseorang. Menjadikan luka itu sebagai ingatan buruk dan pukulan menyakitkan untuk membuat kita semakin jatuh, atau menjadikan luka itu sebagai pukulan semangat dan acuan untuk beranjak dan belajar dari luka. Manapun plihannya, keduanya bukanlah pilihan yang mudah.
Bogor, 26 Mei 2020-
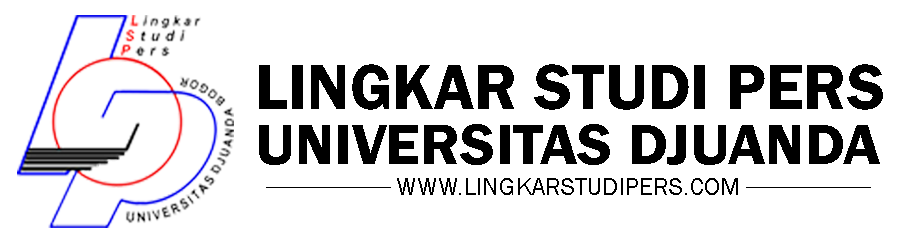



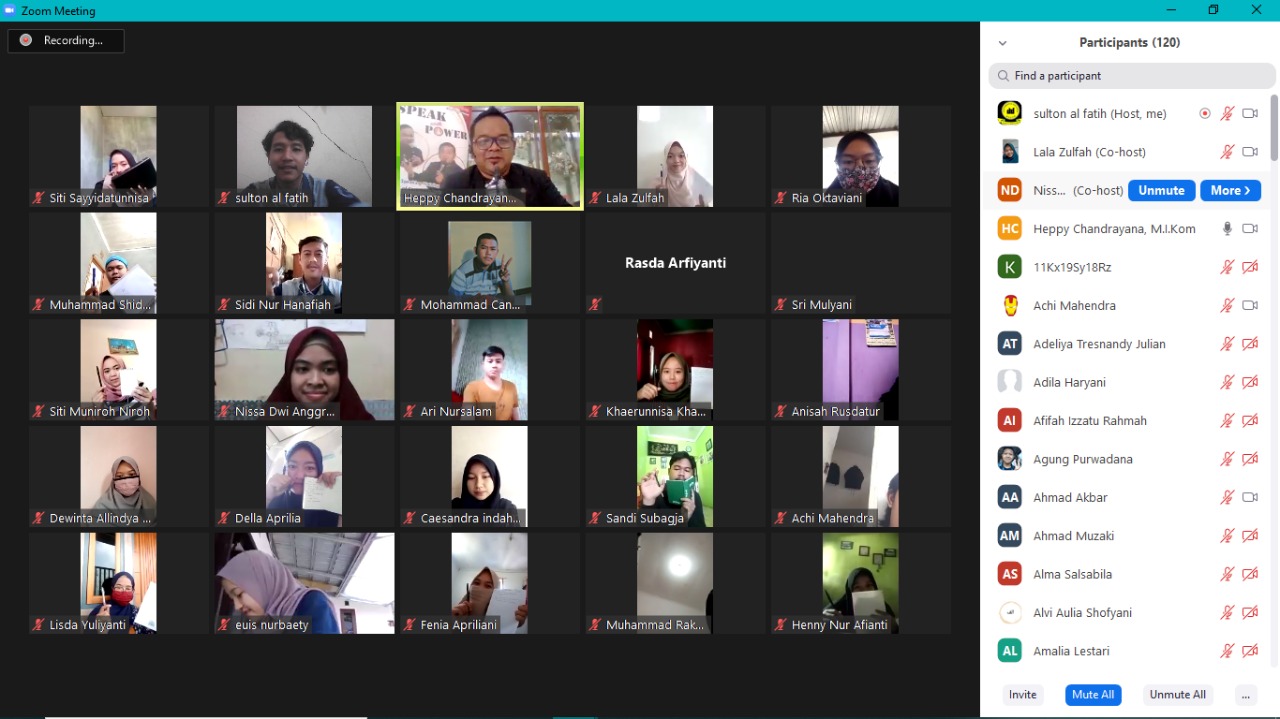











0 Komentar